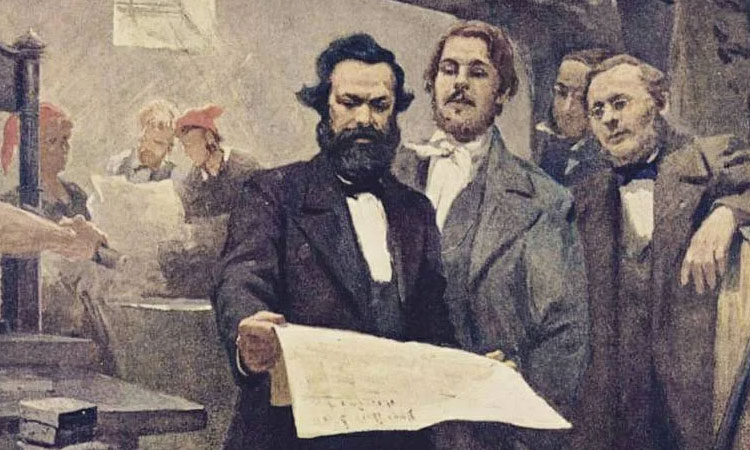
Kata-kata tidak pernah sekadar alat komunikasi. Ia membawa sejarah, nilai, dan cara manusia memandang dunia. Dalam percakapan sehari-hari, terutama ketika bersinggungan dengan pendidikan dan kebudayaan, sejumlah kata tampak sederhana tetapi menyimpan lapisan makna yang panjang. Kata guru, profesor, ustadz, mualim, dan maestro adalah contoh menarik bagaimana bahasa merekam perjalanan pengalaman manusia lintas budaya.
Tulisan ini tidak berpretensi menyusun etimologi ilmiah yang ketat, melainkan sebuah opini yang berangkat dari pengamatan sehari-hari, pengalaman belajar bahasa, dan refleksi atas hubungan antara kata, manusia, serta sejarah peradaban.
Guru dalam Ragam Bahasa dan Budaya
Dalam bahasa Arab, sebutan untuk profesor kerap dilekatkan pada kata ustadz atau ustadzah, sementara untuk guru dalam arti umum digunakan kata mualim. Dalam bahasa Prancis, kata professeur dipakai untuk guru, sedangkan dalam bahasa Italia dikenal kata maestro. Kesan awal terhadap perbedaan istilah ini sering muncul dari pengalaman belajar bahasa populer, misalnya melalui aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo.
Di Indonesia, kata guru memiliki makna yang sangat luas. Guru hadir di sekolah formal, tetapi juga dalam ruang-ruang nonformal dan simbolik. Ada guru pencak silat, soko guru, guru lagu, guru wilangan, hingga guru spiritual. Kata profesor, sebaliknya, cenderung dipersempit penggunaannya untuk menyebut guru besar di perguruan tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya membedakan fungsi, tetapi juga hierarki dan otoritas.
Mahaguru dan Imajinasi Kekuasaan Pengetahuan
Dalam tradisi kanuragan dan persilatan, dikenal istilah mahaguru. Mahaguru bukan sekadar guru yang lebih pintar, melainkan figur tunggal yang memegang otoritas tertinggi. Dalam imajinasi cerita wayang, misalnya, muncul sosok Mahaguru Pandita Durna. Dalam logika persilatan, mahaguru hanya satu, dan pergantian mahaguru bukan perkara administratif, melainkan konflik eksistensial yang bahkan dibayangkan harus “melangkahi mayat mahaguru lama”.
Di sini tampak bahwa kata guru tidak hanya berhubungan dengan pengajaran, tetapi juga dengan kekuasaan simbolik. Bahasa menyimpan imajinasi tentang siapa yang berhak mengajar, memimpin, dan menentukan arah pengetahuan. Topik lainnya: Contoh Parafrase Puisi Ke Prosa
Ustadz, Mualim, dan Ruang Keagamaan
Di Indonesia, kata mualim dikenal tetapi tidak begitu aktif digunakan. Yang lebih dominan justru ustadz dan ustadzah. Namun, dua kata ini tidak digunakan untuk menyebut profesor atau guru akademik, melainkan lebih spesifik untuk guru ngaji dan penceramah keagamaan di kalangan Muslim, terutama yang belum menyandang sebutan kiai.
Pemilahan ini menunjukkan bagaimana bahasa bekerja membatasi wilayah otoritas. Seseorang bisa sangat berilmu dalam bidang tertentu, tetapi sebutan yang melekat padanya tetap ditentukan oleh konteks sosial dan kultural tempat ia berkiprah.
Maestro, Master, dan Aura Ketokohan
Kata maestro di Indonesia dipakai dengan nuansa penghormatan yang kuat. Ia tidak sekadar menunjuk orang yang mengajar, tetapi sosok yang dianggap memiliki kewibawaan, kekuatan, dan kecakapan luar biasa dalam bidang kekaryaan. Nama-nama seperti Basuki Abdullah dalam seni rupa, Pramoedya Ananta Toer dalam sastra, W. S. Rendra dalam teater, atau Chairil Anwar dalam puisi, sering disebut maestro bukan karena jabatan formal, melainkan karena pengaruh dan kualitas karya.
Dalam konteks ini, maestro terasa lebih dekat dengan kata master dalam bahasa Inggris, bukan gelar akademik magister pascasarjana, tetapi master sebagai ahli sejati, seperti Master of Kung Fu atau Master of Ninja. Sekali lagi, bahasa membedakan antara pengakuan administratif dan pengakuan kultural.
Bahasa, Adam, dan Imajinasi Asal-Usul
Jika semua istilah itu dihubung-hubungkan, tampak adanya benang merah yang panjang. Dalam narasi keagamaan, manusia pada awalnya berbagi satu bahasa. Dalam Al-Qur’an, digambarkan bahwa sebelum manusia turun ke bumi, Adam berinteraksi dengan malaikat dan iblis, belajar langsung kepada Tuhan. Adam disebut unggul karena mampu menyebut nama-nama benda yang belum diketahui makhluk lain.
Narasi ini sering dihubungkan secara longgar dengan teori Language Acquisition Device dari Noam Chomsky, yang menyatakan adanya perangkat bawaan dalam otak manusia untuk menciptakan bahasa dan kalimat baru yang belum diajarkan. Meskipun berasal dari ranah yang berbeda, keduanya sama-sama menegaskan keistimewaan manusia dalam berbahasa.
Dari Bahasa Tunggal ke Bahasa yang Banyak
Kisah Adam dan Hawa kemudian dilanjutkan dengan cerita tentang turunnya manusia ke bumi, berkembang biak, dan menggunakan satu bahasa yang sama dalam waktu cukup lama. Dalam tradisi Kristen, dikenal Kisah Menara Babel, tentang kesombongan manusia yang hendak membangun menara menjulang ke langit. Tuhan kemudian mengacaukan bahasa mereka sehingga manusia tidak lagi saling memahami.
Sejak saat itu, pengetahuan bahasa menjadi beragam. Baik melalui narasi keagamaan maupun fiksi antropologis, keragaman bahasa sering dijelaskan sebagai akibat dari peristiwa alam, migrasi, keterpisahan geografis, dan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Bahasa lahir dari cara manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan alam sekitarnya.
Jejak Ilmu Linguistik
Di luar narasi simbolik tersebut, linguistik modern telah lama menelusuri hubungan antarbahasa. Linguistik Historis Komparatif berhasil menyusun silsilah perindukan bahasa, menunjukkan mana bahasa yang berkerabat dan bagaimana perpisahannya terjadi. Sementara Linguistik Kontrastif mengkaji jarak kedekatan antarbahasa untuk menentukan tingkat kesulitan suatu bahasa dipelajari oleh penutur bahasa lain.
Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa keragaman bahasa bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil proses panjang yang dapat ditelusuri secara ilmiah. Bacaan menarik: Besi Wf Pengertian Fungsi Dan Harga
Bahasa, Tubuh, dan Usia
Antropologi linguistik menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya mampu mempelajari bahasa apa pun karena struktur alat ucapnya memungkinkan untuk berkata-kata. Namun, kesulitan mulai muncul ketika bahasa memasuki tahap tulisan. Sistem aksara, simbol, dan konvensi visual menghadirkan tantangan tersendiri.
Selera belajar bahasa pun menjadi beragam. Ada yang tidak menyukai bahasa-bahasa Asia karena kompleksitas hurufnya. Ada pula yang merasa bahasa Prancis memusingkan karena perbedaan antara tulisan dan pengucapan, serta banyaknya huruf yang “harus dibuang” saat berbicara. Sebaliknya, bahasa Spanyol dan Italia sering dianggap lebih ramah, terutama bagi pembelajar yang telah berumur, karena kedekatan antara tulisan dan bunyi.
Namun, usia membawa problemnya sendiri. Kerepotan hidup membuat waktu belajar tidak lagi utuh. Meski demikian, selama rasa senang masih ada, belajar bahasa tetap bisa menjadi ruang kesenangan, entah untuk tujuan apa.
Kesimpulan
Kata guru, profesor, ustadz, mualim, maestro, dan master bukan sekadar label. Ia adalah jejak sejarah manusia dalam memaknai pengetahuan, otoritas, dan pengalaman belajar. Bahasa menyimpan cara manusia menghormati, membatasi, dan mengakui peran seseorang dalam masyarakat.
Pada akhirnya, bahasa bukan hanya alat bicara, tetapi cermin perjalanan manusia itu sendiri: dari satu bahasa ke banyak bahasa, dari satu makna ke ragam tafsir, dari satu peran ke banyak pengakuan. Dan mungkin, di situlah kesenangan belajar bahasa—bukan semata pada kefasihan, tetapi pada pemahaman tentang manusia.







